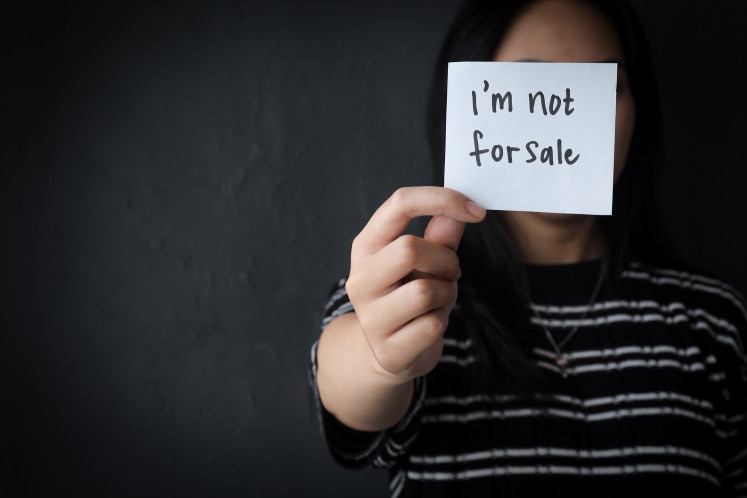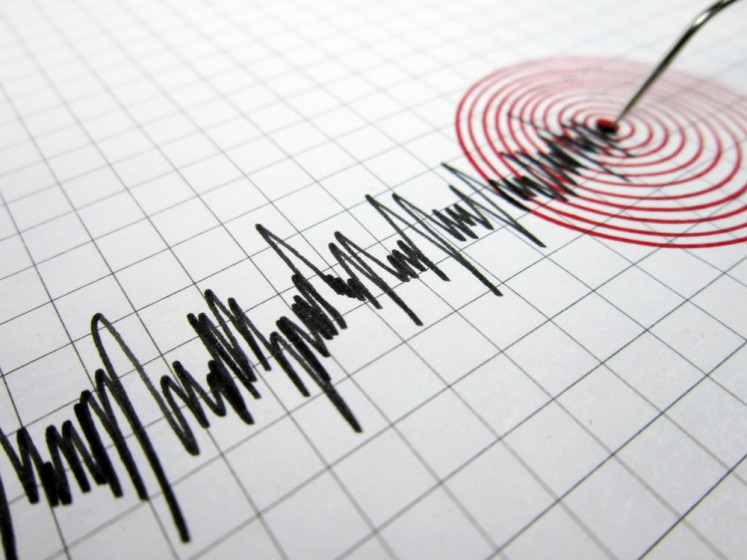Popular Reads
Top Results
Can't find what you're looking for?
View all search resultsPopular Reads
Top Results
Can't find what you're looking for?
View all search resultsKejayaan perdagangan global di masa silam
Pemerintah kita harus bekerja berdasarkan asumsi bahwa perdagangan global sudah berbeda dari yang dulu.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Hampir sebulan setelah Donald Trump memulai masa jabatan keduanya sebagai presiden Amerika Serikat, bisa dipastikan ada perubahan kebijakan perdagangan dari Washington, yaitu dari friendshoring menjadi reshoring.
Di bawah skema friendshoring, pemerintah AS akan mencoba menggunakan pengaruh ekonomi dan politiknya untuk mengubah rantai pasokan global. Perubahan dilakukan sedemikian rupa agar lebih banyak produk dan layanan yang dijual di AS berasal dari negara-negara sekutu, atau berjalan melalui negara-negara “teman”. Konsep ini dijalankan khususnya dalam industri yang secara strategis dianggap penting.
Sebaliknya, reshoring membawa konsep itu selangkah lebih jauh dengan mengembalikan kegiatan manufaktur atau layanan ke AS, setelah sebelumnya kegiatan tersebut dialihdayakan ke negara lain. Biasanya alih daya dilakukan dengan alasan memanfaatkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah di luar AS.
Kebijakan-kebijakan utama di era Biden sudah mengarah ke reshoring. Misalnya, Undang-Undang CHIPS yang menarik produsen semikonduktor dari Asia Timur ke AS, serta Undang-Undang Pengurangan Inflasi yang berupaya menarik investor masuk ke di industri mineral penting, energi bersih, dan kendaraan listrik domestic di AS. Dan Trump semakina memperkuat konsep reshoring hingga dua kali lipat.
Istilah "reshoring" mengasumsikan sudut pandang negara ekonomi maju yang sebelumnya "mengalihdayakan" produksi ke negara-negara berkembang. Namun sesungguhnya, motivasi untuk reshoring, yaitu agar sebuah negara menjadi lebih mandiri sekaligus mampu menciptakan lapangan kerja di dalam negeri, berlaku juga untuk negara dengan ekonomi yang sedang berkembang seperti Indonesia.
Jakarta harus bersimpati dengan kebijakan reshoring yang dijalankan Washington, karena kita juga bercita-cita memproduksi segala yang bisa kita produksi di dalam negeri, dan tidak mengonsumsi barang dan jasa dari negara lain. Hampir setiap hari ada pejabat yang mengeluh soal "banjir impor" dari Tiongkok.
Keinginan kita untuk jadi tuan rumah di negeri sendiri dapat dimengerti, meskipun kita akan lebih banyak buntung ketimbang untung jika reshoring jadi kebiasaan baru. Alasannya, negara-negara berkembang seperti kita telah lama menikmati arus masuk investasi asing langsung yang besar dari perusahaan-perusahaan global. Mereka membangun pabrik di Indonesia, memproduksi barang-barang untuk diekspor.
Masalah kita adalah bahwa tenaga kerja murah tidak lagi laris manis seperti dulu. Saat ini, pabrik-pabrik hanya butuh sebagian kecil saja dari tenaga kerja yang mereka perlukan di masa 20 atau 30 tahun yang lalu.
Dengan meningkatnya otomatisasi, hitungan biaya tenaga kerja hanya menyumbang sedikit saja dalam biaya per unit. Sementara komponen energi dan bahan baku menyumbang porsi yang lebih besar di total biaya.
Masih belum jelas apakah globalisasi sedang menuju ke arah yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Tetapi saat ini, globalisasi terlihat tidak bagus. Jadi, pemerintah kita sebaiknya bekerja dengan asumsi bahwa perdagangan global berbeda dari yang dulu.
Artinya, kita tidak dapat meniru mentah-mentah kebijakan Vietnam yang menggunakan strategi China+1.
Vietnam menempatkan diri sebagai basis produksi alternatif bagi perusahaan yang ingin melakukan diversifikasi dari Tiongkok. Hal itu dilakukan agar Vietnam dapat mempertahankan akses ke pasar Barat, bahkan jika pemerintah Barat memberlakukan larangan atau menaikkan tarif atas barang-barang dari Tiongkok.
Strategi itu tidak akan berhasil lagi jika AS, Eropa, dan pasar-pasar utama lainnya beralih dari friendshoring ke reshoring.
Sebaliknya, kita harus meningkatkan industri manufaktur kita. Jadi, meskipun kita tidak dapat mengandalkan pasar ekspor, setidaknya kita dapat memproduksi barang-barang yang harganya kompetitif untuk pasar kita sendiri, dalam sebuah konsep yang dikenal sebagai substitusi impor.
Pasar domestik yang besar adalah kekuatan kita. Pemerintah sangat menyadari hal itu dan telah menggunakan argumen itu untuk menarik investasi.
Pada saat yang sama, saat pintu-pintu perdagangan global mulai menutup, kita bisa menjaga terbukanya pintu perdagangan di kawasan.
Jika ASEAN atau Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (Regional Comprehensive Economic Partnership atau RCEP) dapat menegakkan prinsip-prinsip David Ricardo berdasarkan keunggulan komparatif, kawasan kita bisa saja jadi magnet bagi investasi dari perusahaan-perusahaan yang mencari kejayaan seperti di masa lalu.