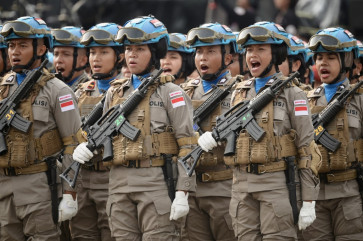Popular Reads
Top Results
Can't find what you're looking for?
View all search resultsPopular Reads
Top Results
Can't find what you're looking for?
View all search resultsPengkhianatan terhadap ‘Reformasi’
Sungguh menyedihkan bahwa kita melihat memudarnya semangat reformasi tidak hanya di dunia politik kita, tetapi juga di lembaga peradilan.
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone
Jika kita membiarkan Presiden Prabowo Subianto melakukan yang ia inginkan, yaitu mereformasi undang-undang pemilihan kepala daerah, kita akan mengkhianati semangat reformasi politik yang telah mengubah Indonesia menjadi negara demokrasi. Kita sudah beusaha sekuat tenaga hingga membayar dengan darah, keringat, dan air mata untuk memperjuangkan reformasi, dan mewujudkannya, demi mengakhiri lebih dari tiga dekade kediktatoran Soeharto pada 1998.
Usulan Prabowo untuk kembali ke mekanisme pemilihan tidak langsung saat memilih kepala pemerintahan daerah tidak hanya akan merampas kedaulatan rakyat. Usul itu, jika terlaksana, bertentangan dengan upaya desentralisasi yang merupakan bagian tak terpisahkan dari reformasi, untuk memberi lebih banyak otonomi kepada daerah.
Setelah jatuhnya Soeharto, ada semacam konsensus nasional bahwa kita tidak boleh membiarkan negara ini kembali jatuh ke dalam otoritarianisme. Kini, kami jadi merasa sangat terganggu bahwa sebagian besar partai politik dalam pemerintahan koalisi Prabowo, yang menguasai DPR, secara terbuka mendukung usulan Presiden untuk mengubah undang-undang pemilu.
Usulan Prabowo tersebut menyerukan agar kepala pemerintahan daerah, termasuk gubernur, bupati, dan wali kota, dipilih oleh dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Jadi, pemilihannya bukan secara langsung oleh rakyat seperti yang telah terjadi selama 20 tahun terakhir.
Ketika DPR mulai membahas RUU pemilu, kami berharap cukup banyak partai yang akan berjuang habis-habisan dalam mempertahankan demokrasi dan otonomi daerah, yang telah susah payah diraih. Mereka akan berjalan bersama dorongan dari masyarakat sipil, seperti yang terjadi selama tahun-tahun awal reformasi,
Undang-undang pemilu kepala daerah rentan karena konstitusi menyatakan bahwa kepala pemerintahan daerah harus dipilih melalui proses yang demokratis. Putusan Mahkamah Konstitusi pada 2013 menafsirkan bahwa hal ini berarti pemilihan langsung merupakan perwujudan kedaulatan rakyat.
Sayangnya, kita melihat semangat reformasi mulai memudar, tidak hanya di tubuh partai politik kita, tetapi juga di lembaga peradilan. Sebagian kaum elite politik bahkan memanfaatkan pendeknya ingatan masyarakat, yang sepertinya telah jadi kutukan bangsa kita.
Kami sangat setuju dengan Prabowo tentang perlunya memangkas biaya penyelenggaraan pemilu yang sangat besar. Lebih-lebih, tahun ini pemilu terasa sangat memberatkan secara finansial, karena untuk pertama kalinya, kita menyelenggarakan beberapa pemilu dalam setahun. Pada Februari, kita menyelenggarakan pemilihan presiden, wakil presiden, serta anggota DPR dan DPD, juga anggota dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Pada November, kita menyelenggarakan pemilihan kepala daerah.
Demokrasi berskala Indonesia, dengan jumlah penduduk 280 juta jiwa, pasti mahal. Jika kita menginginkan efisiensi biaya, Bapak Presiden, Anda salah kaprah kalau hanya memangkas proses salah satu pemilu ini. Anda tidak boleh mengorbankan kedaulatan rakyat.
Demokrasi menjadi mahal di Indonesia, bukan karena skala atau jumlah pemilihan umum, tetapi lebih karena meluasnya praktik "politik uang". Lihat saja, semua perlu uang, mulai dari jual-beli suara dan "serangan fajar” saat kandidat membanjiri pemilih dengan hadiah di pagi hari sebelum jam pemilihan, hingga persaingan antar kandidat untuk saling mengalahkan dalam hal dana kampanye. Lebih jauh, tidak ada kontrol dan audit keuangan kampanye yang efektif. Jika Anda menangani masalah-masalah ini, Bapak Presiden, Indonesia dapat melakukan penghematan yang signifikan.
Yang paling mengganggu dari usulan untuk mereformasi undang-undang pemilu adalah kenyataan bahwa kita melihat tren yang konsisten menuju otoritarianisme.
Beberapa partai politik, termasuk Partai Gerindra milik Prabowo sendiri, telah secara terbuka menyerukan agar negara ini kembali ke pemilihan umum tidak langsung untuk presiden dan wakil presiden. Hal itu persis yang dilakukan negara saat dipimpin oleh Soeharto. Konstitusi, yang telah diamandemen, menyatakan bahwa presiden atau wakil presiden harus dipilih oleh rakyat. Ini mungkin tampak lebih sulit untuk dilakukan daripada mengubah undang-undang pemilihan kepala daerah, tetapi itu bukan hal yang mustahil. Mengingat dominasinya di legislatif, pemerintah dapat dengan mudah mendorong amandemen konstitusi.
Jika berhasil mengubah UU pemilihan kepala daerah, setelahnya tidak ada yang bisa menghentikan pemerintah untuk melakukan perubahan lain yang lebih besar. Dalam waktu dekat, kita bisa kembali dikutuk oleh otoritarianisme. Tidak ada pengkhianatan yang lebih besar terhadap kedaulatan kita daripada menyaksikan perubahan ini melalui "proses demokrasi" yang kita susun selama reformasi.