Popular Reads
Top Results
Can't find what you're looking for?
View all search resultsPopular Reads
Top Results
Can't find what you're looking for?
View all search resultsPatrimonialisme baru
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone

Telah seperempat abad rezim Orde Baru baru tergantikan. Tahun depan, Indonesia sudah akan mengadakan pemilihan umum lagi. Dengan segala persiapan yang terjadi saat ini, kita punya banyak alasan untuk percaya bahwa segala sesuatu berjalan baik dan menuju arah yang benar.
Lalu, kita sudah punya tiga pasangan calon presiden dan wakil presiden yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Akhir pekan ini, KPU dijadwalkan akan mengumumkan secara resmi bahwa ketiga pasangan layak mencalokan diri menjadi kandidat untuk pemilihan umum tahun depan.
Namun, betapapun optimisnya kita terhadap prospek pemilu dan gerakan reformasi yang sedang berlangsung, saat ini tampaknya tepat untuk melihat kembali dan belajar jika ada yang salah dengan rezim Orde Baru.
Gaya otoritarianisme Soeharto menganut efisiensi yang kejam. Para pakar menyebutnya sebagai sistem patrimonialis. Dengan sistem tersebut, sang pemimpin secara ekstensif memanfaatkan patronasi untuk menjamin kesetiaan bawahannya, juga kesetiaan para anggota elit nasional. Sistem tersebut juga membuat pemimpin menerapkan kekuatan koersif yang hebat sebagai panglima tertinggi militer (dengan aparat intelijen yang sangat banyak).
Keruntuhan Rezim Orde Baru dimulai dari dalam, ketika Soeharto tak lagi punya sumber daya ekonomi untuk menyuap para anggota elit di Jakarta. Ini salah satu akibat krisis keuangan pada akhir 1990an. Saat itu, dukungan militer memisahkan diri dari rencana pembunuhan yang dirancang Soeharto.
Patronasi dan penerapan kekuasaan koersif negara masih terjadi di masa reformasi. Namun, politik menjadi sangat terpecah belah dalam sistem multi-partai saat ini sehingga tidak ada satu pun pemimpin politik yang mampu memanfaatkan keduanya secara efektif, sampai Presiden Joko “Jokowi” Widodo terlibat.
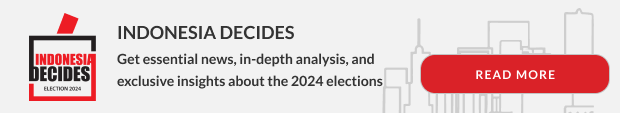
Kini, setelah dua masa jabatan Presiden, kita menghadapi kemungkinan kembalinya praktik patrimonial Orde Baru sepenuhnya.
Banyak percakapan soal pembagian sumber daya terkait elit nasional yang bersekutu dengan Presiden. Inisiatif hilirisasi yang dilakukan Presiden dan upaya infrastruktur besar-besaran yang dilakukannya tentu saja memberi cukup keuntungan bagi sebagian pendukungnya.
Namun, kita patut khawatir atas perkembangan terkini. Negara ini mungkin sedang memasuki yang digambarkan Max Weber sebagai bentuk patrimonialisme ekstrem. Sebagian orang menyebut hal tersebut sebagai “sultanisme”. Dalam konsep tersebut, “dominasi tradisional mengembangkan kekuatan administratif dan militer sebagai hal yang murni merupakan instrumen dari si majikan.”
Saat ini, ketika negara masuk proses pemilihan umum tahap berikutnya, dapat kita katakan bahwa kekuatan administratif dan militer—termasuk Kepolisian Nasional—telah diubah jadi instrumen politik.
Nasib politik Presiden Jokowi dan putranya bergantung pada kemenangan koalisinya dalam pemilihan presiden tahun depan. Karena itu sangat mudah melihat arah intrik yang ada saat ini terkait tokoh di balik layar yang mengendalikan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri.
Mengapa Presiden memutuskan mempercepat pencalonan Jenderal Agus Subiyanto sebagai Panglima TNI, hanya enam hari setelah ia dilantik jadi Kepala Staf Angkatan Darat?
Bagaimana jika sang jenderal sudah dirancang untuk menduduki jabatan tersebut sejak bertahun-tahun silam, hanya karena dia punya hubungan dekat dengan Presiden saat sang pemimpin menjabat sebagai Wali Kota Surakarta?
Bagaimanapun, kepemimpinan Polri telah berada di tangan loyalis lain yang juga dekat dengan Presiden, yang sudah merintis kedekatan sejak masa jabatannya di Surakarta.
Kita paham bahwa Agus adalah seorang Jenderal yang profesional dan berkualitas untuk memangku jabatan Panglima TNI. Kita percaya ia akan menepati sumpah jabatannya. Namun jika terjadi keadaan darurat nasional terkait pemilu tahun depan, apakah dia akan mengambil tindakan tanpa memikirkan hubungan dekatnya dengan Presiden?
Pertanyaan serupa tidak pernah kita ajukan selama ini, karena selama masa reformasi, militer tidak pernah terlibat dalam politik Militer selalu netral dalam beberapa pemilu yang telah lau. Mari pertahankan netralitas tersebut.










