Popular Reads
Top Results
Can't find what you're looking for?
View all search resultsPopular Reads
Top Results
Can't find what you're looking for?
View all search resultsSuara NU tak bisa dibeli
Change text size
Gift Premium Articles
to Anyone

Kita tidak boleh menganggap remeh peran penting Nahdlatul Ulama (NU) dalam pemilihan presiden mendatang. Bukan hanya karena NU mewakili mayoritas umat Islam di Indonesia, tapi juga karena NU mewakili semua, bahkan yang bukan anggotanya.
Secara elektoral, posisi NU penting, terutama karena NU merupakan kelompok yang berpengaruh bagi pemilih di Jawa Timur. Provinsi tersebut menjadi medan yang diperebutkan, dan tidak ada satu pun dari bakal calon presiden, mulai dari Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies Baswedan, yang punya basis kuat di sana. Tak heran jika tokoh-tokoh NU masuk dalam daftar calon wakil presiden terkuat, karena mereka dianggap sebagai penggalang suara tertinggi.
Anies, misalnya, memilih pemimpin Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Langkah Anies adalah sebuah langkah politik rasional dan praktis, meski tetap mengejutkan banyak orang. Keterkejutan lebih karena mengingat bahwa selama bertahun-tahun mantan gubernur Jakarta itu mendukung kelompok-kelompok Islam yang ideologi transnasionalnya sebagian besar sejalan dengan pandangan NU.
Prabowo dan Ganjar telah mempertimbangkan beberapa tokoh NU untuk jadi pasangan mereka. Nama yang muncul sebagai calon cawapres, misalnya, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa, dan Yenny Wahid, putri mantan presiden dan Ketua NU Abdurrahman “Gus Dur” Wahid. Bukan tidak mungkin pemilu tahun depan bisa menjadi ajang kompetisi tokoh NU.
Bukan hal yang aneh bagi politisi untuk memobilisasi sentimen rasial, agama, dan nasionalis demi menggalang suara, yang jadi dosa asli politik identitas. Pada dasarnya, strategi tersebut tidak bermoral, terutama ketika politik identitas digunakan untuk membebaskan sekelompok orang yang telah terpinggirkan secara struktural, politik, dan ekonomi.
Di sisi lain, sulit untuk mengabaikan pragmatisme elit politik dalam mengeksploitasi sentimen NU untuk tujuan pemilu jangka pendek mereka. Salah satu contohnya adalah gambaran Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir sebagai anggota NU setelah bergabung dengan kelompok pendukungnya, Banser. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno juga mendapat label “NU” setelah bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), yang pernah menjadi satu-satunya saluran politik berbasis Islam, termasuk untuk anggota NU.
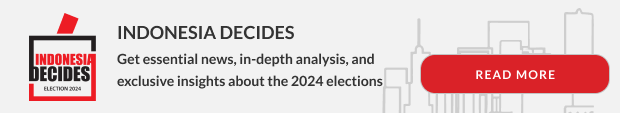
Hal ini tentu saja mengkhawatirkan bukan hanya bagi NU, namun juga bagi demokrasi kita. Terbayang bahwa saat ini NU menjadi organisasi utama yang konon memainkan politik identitas. Ketika organisasi-organisasi revivalis seperti Front Pembela Islam (FPI), Hizbut Tahrir Indonesia, dan kelompok Salafi yang terkait dengan gerakan 2/12 kehilangan kekuatan, NU kini jadi satu-satunya instrumen politik yang dapat digunakan para elit untuk merebut kekuasaan.
NU mendapat pujian tidak hanya sebagai garda depan Islam moderat tetapi juga sebagai tulang punggung demokrasi kita. Sebagai kelompok masyarakat sipil yang memperjuangkan nilai-nilai pluralisme dan pandangan keagamaan yang progresif, NU terlalu penting untuk sekadar dijadikan alat pemilu oleh para elit politik.
Ketua NU Yahya Cholil Staquf menegaskan bahwa NU adalah kelompok masyarakat sipil yang beroperasi di luar partai politik. Pernyataan yang menggembirakan, namun kita perlu mengingatkannya bahwa pernyataan tidak selalu jadi bukti komitmen.
Secara historis, NU selalu menjadi bagian dari politik Indonesia, tidak hanya di tingkat akar rumput tetapi juga di tingkat elit. Pertanyaannya adalah apakah Yahya bisa menahan godaan untuk bermain politik, dengan kekuasaan yang ia miliki sebagai pemimpin senior NU.
Segera setelah Muhaimin mendeklarasikan pencalonannya sebagai wakil presiden, Yahya dengan cepat menyatakan bahwa tidak ada calon politik yang bisa mengaku mewakili NU. Kakak laki-laki Yahya, Yaqut Cholil Qoumas, yang menjabat Menteri Agama, meminta masyarakat untuk tidak memilih kandidat yang “memecah belah”. Jelas ia merujuk pada Anies, yang dituduh menggunakan retorika sektarian untuk memenangkan pemilihan gubernur Jakarta pada 2017 silam.
Jika dilihat langsung, pernyataan macam itu tampak aman secara politik. Namun, pernyataan demikian bisa jadi problematis karena Yaqut dekat dengan Erick, yang potensial menjadi calon wakil presiden Prabowo. Juga karena Ganjar telah bertemu dengan ibunda Yahya dan Yaqut, dan pertemuan tersebut tentu jadi bagian dari tur politik.
Kita harus menunggu bukti sebelum yakin bahwa Yahya akan melindungi NU dari segala bentuk politik predator. Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan hanya kredibilitas NU sebagai benteng moralitas, tapi juga nasib demokrasi kita.









